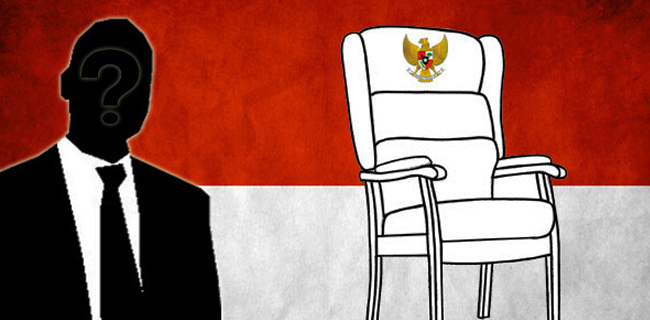Pilpres, jadinya hanya sekadar politik menang dan kalah, pertempuran pihak baik dan pihak jahat, dengan level kekejaman yang memukul telak akal sehat. Menang dan kalah menjadi premis dasar pilpres.
Pemenang menguasai semuanya dan pihak yang kalah tersingkir dalam segala hal. Itulah realitas politik pilpres demokratis. Paradoksnya pilpres jenis ini disanjung sebagai anak peradaban terhebat sepanjang waktu.
Berulang
Tidak ada prasangka, caci maki, kegaduhan, fitnah, tuduhan keji, berita rasis, merendahkan agama, dan lainnya di Amerika ketika George Washington dipilih menjadi presiden untuk pertama kalinya pada tahun pada 1789. Tak juga pada periode jabatan untuk kedua kalinya pada 1794. Keanggunan ini, manisnya, berlanjut ke pilpres ketiga yang menghasilkan John Adams sebagai presiden kedua Amerika.
Tetapi semuanya berubah pada pemilihan presiden untuk keempat kali dalam sejarah Amerika. Pada pilpres ini John Adams, wapres Washington dan Thomas Jefferson, menlu Washington, harus berhadapan sebagai sesama capres. Fitnah pun bermunculan, menghebohkan jagat politik pilpres kala itu.
Keadaan ini ditulis Denise A. Spilberg, wanita bergelar profesor sejarah dan Timur Tengah pada Universitas Texas. Kampanye presiden John Adams melawan sang penantang Thomas Jefferson pada pemilihan tahun 1800, tulis Denise, adalah “kampanye kotor†pertama dalam sejarah pemilu Amerika.
Saat itulah kali pertama, tetapi bukan kali terakhir, calon presiden dituduh menjadi seorang muslim. Keyakinan agama dari anggota partai Republik Jefferson, Denise melanjutkan, menjadi pusat sasaran serangan kelompok Federalis, dengan Jefferson digambarkan secara keliru sebagai seorang ateis dan, lebih akurat lagi, seorang penganut Deisme.
Terkadang, Denise menulis, dia juga disebut sebagai seorang “kafir†sebuah istilah yang menunjukan tidak hanya orang yang telah menolak agama Kristen, tetapi juga seorang penganut agama yang menentang agama Kristen, secara spesifik seorang muslim.
Pilpres itu berakhir dengan kekalahan John Adams, dan Jefferson keluar sebagai pemenang. Sialnya lebih dari satu abad sesudah peristiwa Jefferson, ketika Amerika tiba pada pemilihan presiden tahun 2008 beredar laporan-laporan palsu tentang Senator Barrac Obama seorang Muslim “diam-diam†tulis Denise, mulai beredar tepat setelah pidatonya yang mengesankan dalam Konvensi Nasional partai Demokrat pada 2004, jauh sebelum seorang muslim sungguhan, Keith Ellison, menjadi kandidat anggota Congres.
Sebuah Surel anonim, tulis Denise selanjutnya, yang dibuat oleh seorang agen politik Partai Republik pinggiran yang menggambarkan dirinya sebagai orang “independen†menyebarkan sederet kebohongan bahwa; Obama menyembunyikan fakta dia seorang muslim, bahwa ayah tirinya “memperkenalkan anak tirinya pada Islamâ€; bahwa dia terdaftar disebuah sekolah Islam di Indonesia, tempat dia belajar “ajaran radikal yang diikuti teroris Muslim.â€
Penulis surel tersebut, tulis Denise, juga dengan sengaja menyebutkan Obama sebagai “Osama.†Tuduhan tersebut akan beredar lebih luas di Web pada 2006, saat Obama secara aktif mempertimbangkan tawaran kepresidenan. Pada tahun 2007, “CNN dan lain-lain†telah sepenuhnya menepis penodaan tersebut, tetapi sebagaimana dilaporkan Cris Hayes, “tuduhan palsu awal jelas telah meresap ke dalam kesadaran masyarakat.â€
Benar ketika pemilu tiba, dalam rapat akbar di Minesota, seorang wanita pendukung Senator McCain lawannya Obama secara terbuka mengatakan "Saya tidak percaya Obama."
Tetapi McCain segera mengambil mikrofon dan mengatakan, tidak bu. Dia seorang pria dari keluarga baik-baik (dan) warga negara yang kebetulan saja saya berbeda pendapat dengannya menyangkut permasalahan fundamental, dan itulah alasan kampanye ini.
Kepresidenan Obama berakhir dan Amerika menempatkan Hillary Clinton dan Trump di panggung pilpres. Apa yang terjadi? Surel-surel Hillary Clinton, capres yang pernah menjadi Ibu Negara dan menteri luar negeri pada pemerintahan Barrack Obama, diselidiki FBI. Hillary dituduh pro Wall Street, dan bukan hanya Trump, tetapi Melania, istrinya dibombardir berita tentang masa lalunya. Tidak itu saja FBI juga menyelidiki, berdasarkan dugaan, kemungkinan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden itu.
Menimbang Kembali Seperti yang sudah-sudah sejak tahun 2004, pilpres kita juga sama, diselimuti prasangka rendahan, fitnah, berita bohong dan hal lainnya yang sejenis, yang semuanya menyepelekan akal sehat.
Derajat pilpres terlihat tidak lebih dari sekadar permainan tanpa takaran akal yang terbimbing oleh nilai-nilai civilian. Kerangka kerja, bukan hanya konstitusi, hukum organikpun, pada level tertentu terlihat kehilangan keandalannya.
Semuanya, pada level tertentu, nampak menjadi aksioma alamiah pilpres. Mengapa? Selalu begitu, berulang dan berulang setiap kali pilpres tiba. Intensitasnya kian menjadi-jadi, menggila, mendekatkan bukan pada civilian society, yang menempatkan kesantunan sebagai bimbingan, tetapi pada keadaan yang dibimbing etika situasional.
Padahal akan terasa indah andai pilpres tersajikan dan direspons sebagai panggung monumental ditemukannya jawaban-jawaban bijaksana tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Indah dan mengagumkan bila pilpres tersajikan sebagai medan solusi masalah-masalah bangsa yang perlu diperbicangkan dengan terhormat, yang memungkinkan khalayak merancang preferensinya.
Toh pilpres dirancang secara konstiusional sebagai medan, selain menemukan presiden baru atau mempertahankan pemerintahan yang sedang berkuasa, yang diputuskan oleh pemilih. Pilpres, dengan demikian menjadi medan pengujian atas keadaan nyata dan gagasan baru, berorientasi penciptaan kehidupan yang bermartabat.
Sayangnya pilpres langsung, cukup jelas, sejauh ini tak cukup menyediakan energi membuat indah pesan alam betapa fitnah, prasangka, berita bohong justru memukul kemanusiaan, diri sendiri, kini dan kelak disuatu hari nanti.
Semua keburukan itu, andai dapat ditunjuk sebagai guru yang membimbing, maka menemukan pilpres dengan cara lain yang bermartabat, yang tak merobek-robek kemanusiaan dan akal sehat, relefan dipertimbangkan. [***]
Penulis: Doktor HTN, Staf Pengajar pada FH Universitas Khairun Ternate