Sedulur sikep, nama lain masyarakat Samin, ini sedang mempertahankan keyakinan atas apa yang mereka maknai sebagai barang milik pribadi.
Motor dibeli dengan uang sendiri, dari hasil kerja sendiri, bukan pemberian orang apalagi negara, bukan hasil mencuri, dipakai sendiri dan kalau rusak dibayar dari dompetnya sendiri. Dengan semua alasan itu, motor bagi orang Samin adalah barang milik pribadi, bukan milik negara.
Lalu mengapa dipajaki? Memajaki apa? Jalan? Membangun jalan kewajiban negara, seperti kewajiban warga menjaganya. Dari mana uang untuk membangun dan memeliharanya kalau tidak dari pajak?
Tidak. Tidak begitu, Tuan Baron. Itu salah! Kalau kami saja bisa bekerja mencari uang, mengapa negara tidak bekerja keras mencarinya? Negara sangat pintar soal ini, banyak ahlinya, tinggal bayar, kami tidak mau menggurui negara teknik mencari duit.
Bukankah orang-orang yang bekerja di lembaga negara itu berasal dari rakyat? Orang tua rakyat itu, kalau tidak menjadi pegawai negara, berarti pernah bekerja dan mengajari anak-anaknya bekerja.
Lalu mengapa setelah menjadi pegawai justru malas bekerja? Memajaki tanpa kerja, palak namanya.
Begitu cara berpikir masyarakat Samin. Logis. Simpel. Tidak menggerakkan apa pun. Satu-satunya alasan sehingga layak disebut gerakan adalah menggerakkan logikanya sendiri. Keyakinan yang diam-diam punya ujung sejarah.
Begini, sejak konsep negara modern muncul, apa yang dianggap logis menurut masyarakat Samin terkoreksi setelah pemimpin yang mengurus negara diberi kuasa atas negeri dan warga yang dikuasainya.
Warga menurut negara adalah pengontrak rumah di tanah milik negara. Ini dijelaskan oleh Hobbes, Locke, atau Rousseau dalam teori kontrak sosial.
Sebagai pengontrak, ia harus bayar sewa. Itu pajak namanya. Konsep itu bersumber dari ujungnya pemikir: Plato dan Aristoteles. Di ujungnyanya lagi tidak ada. Di situ masyarakat Samin ingin diperlakukan sebagai warga.
Maka, jadilah motor-motor di sana dulu berseliweran dengan tahun kadaluarsa. Kalau sekarang masih ada, tidak usah jauh-jauh datang ke komunitas Samin di Pati, Kudus, atau Blora.
Tetangga kita yang tukang ngarit saja tak pernah meremajakan plat nomornya sejak dibeli.
Menderu dengan asap hitam mondar-mandir mengusung rumput di hanya seputaran sawah. Dengan rokok menjuntai di bibir pula. Seperti tidak punya negara, katamu, jika engkau pegawai negara.
Bagaimana meletakkan gerakan anti-bayar pajak dalam konsep negara modern dan demokratis macam Indonesia?
Rakyat dalam konteks ini adalah pihak pengontrak atau penyewa, yang kalau rumah yang disewanya buruk, ia akan meminta pemiliknya memperbaiki, baik infrastrukfur atau pelayanan non-fisik lain.
Itu kritik namanya. Layaknya konsumen premium, ia raja diraja dari pembuat dan pelaksana kebijakan di rumah kontrakannya itu.
Bedanya, pengontrak biasa bisa memilih pergi dengan mudah dan memilih rumah lain yang lebih cocok jika terjadi perselisihan. Sedang, warga negara tidak semudah pindah negara atau propinsi.
Sebagai pengontrak rumah dalam teori itu, rakyat bukan semata penyewa, tetapi pemilik kontrakan itu sendiri. Pemilik saham terbesar negara ini.
Ia menyerahkan mandatnya melalui mekanisme Pemilu dan SOP kenegaraan, baik ke presiden, gubernur, bupati, bahkan anggota parlemen, hakim, TNI, polisi, dan jaksa.
Pejabat di tingkat apa pun hanya CEO, direktur, manager dan pegawai-pegawai yang harus tunduk pada mandat rakyat. Agar benefit dan profitabilitasnya bisa kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas dan kesejahteraan.
Sebutlah saran masyarakat Samin untuk bekerja mencari uang diikuti. Didirikan BUMN dan BUMD. Tapi, lihat yang terjadi. Hampir semua perusahaan negara rugi, kolaps dan akhirnya dijual ke swasta.
Uniknya, swasta ini seperti masyarakat Samin yang mandiri. Bekerja dengan benar dan menyulap BUMN yang dulu rugi menjadi laba. Telkom, Bank Mandiri, misalnya.
Lalu di mana letak kesalahannya? Di profesionalitas dan efisiensi. Dua hal yang sering disorot para ahli.
Kesalahan-kesalahan ini diperpuruk oleh kebobrokan mental pegawai yang mengorupsi modal usaha sebagai babon dan nyawa dari makhluk bernama bisnis. Langsung mati kalau disedot dari sini.
Hebatnya, selalu ada cara menyuntik obat sebelum mati dengan cara negara menggerojok modal lagi. Pakai apa? Pakai uang pajak rakyat itu.
Kalau tidak ada, utang dulu pakai SUN. Yang bayar nanti rakyat juga. Berputar-putar di situ. Seolah negara memiliki cadangan nyawa yang tidak pernah habis.
Dampaknya, mengambil nyawa warganya. Mati anak SD di NTT, mati pemotor di jalan karena bergelombang, dan entah nanti di mana lagi menyusul kematian atas nama ketidakcukupan uang untuk melayani sang pemilik saham.
Dalam ekosistem ekonomi yang tidak support seperti Indonesia, negara sulit menabung devisa dan karena itu andalan termudahnya pajak dan tambang.
Ekosistem itu antara lain komponen dan bahan baku industri yang masih bergantung impor, bahan baku melimpah tapi belum bisa mengolah, ketrampilan warga dalam bidang STEM tidak terupdate karena anggaran tersedot program lain yang tidak mendesak, aturan usaha yang birokratis, sampai ke soal penegakan hukum yang timpang, dst.
Maka, memahami gerakan anti-bayar pajak itu perlu didekati dalam dua konteks itu: sebagai kritik atas pelayanan publik oleh pemilik saham terbesar negara ini, dan oleh ketiadaan sumber devisa, sehingga sumber terdekat dan termudahnya adalah pajak.
Sumber devisa lain dari pemerintah pusat yang diandalkan di tengah ketiadaan sumber ini sudah setahun lebih disedot untuk salah satunya program MBG.
Pengetatan anggaran terjadi karena pengalihan ini. Buat daerah, ia sebab sekaligus akibat. Wajar beberapa kepala daerah, kalau saja bebas mengkritik, akan mengajukan keberatan atas program ini.
Jadi, Pak Gubernur, gerakan anti-bayar pajak kendaraan bermotor ini saya yakin bukan sedang mengancam, tapi hanya merajuk. Mereka mencintai Anda.
Meminta agar Anda dan timnya atasi pelayanan publik dengan baik. Sat-set, dan putuskan sendiri jangan terlalu lama menunggu kerja tim.
Tim itu menunggu Anda memberi sinyal. Putuskan sekarang seperti gubernur sejawat Anda, dengan segala kebaikan dan kekurangannya, bertindak sangat cepat. Sebelum rakyat kecewa dan memproduksi entah aksi apalagi di sosial media.
 Hasan AoniPenulis
Hasan AoniPenulis
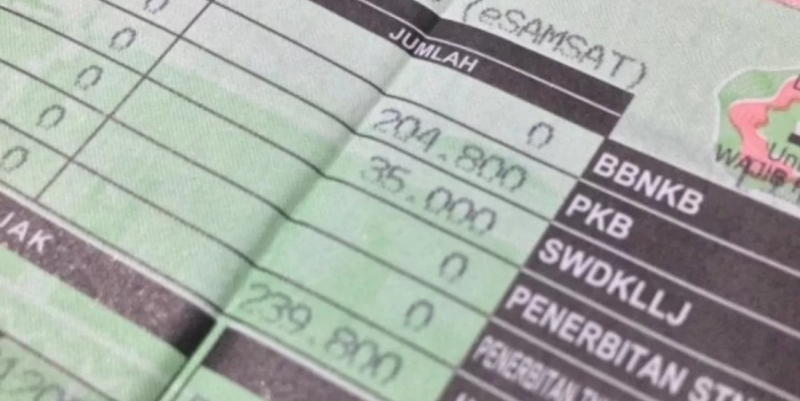

BERITA TERKAIT: